Efek lanjutan dari pola tersebut adalah krisis legitimasi moral, terutama di mata pemilih muda yang semakin kritis di awal 2026. Publik mampu membedakan antara pengabdian yang tulus dan pembelaan yang bermotif pengamanan posisi. Ketika etika dikendurkan demi kebersamaan semu, organisasi politik sejatinya sedang mempertaruhkan kredibilitas sejarahnya sendiri.
Romadhon Jasn menilai bahwa “normalisasi dalih ‘salah paham konteks’ adalah bentuk ketidakberanian intelektual untuk mengakui kesalahan; kewajiban moral kepada pimpinan tidak boleh mengalahkan kewajiban moral kepada kebenaran yang bersifat universal.” Pandangan ini menegaskan bahwa loyalitas sejati tidak pernah bertentangan dengan kejujuran moral.
Publik sejatinya masih menaruh keyakinan bahwa para petinggi partai yang rasional tidak menghendaki dalih serendah ini menjadi wajah kaderisasi mereka. Namun dalam lanskap politik digital, persepsi dibentuk bukan oleh niat tersembunyi, melainkan oleh tindakan nyata dan konsekuensi yang tampak di ruang publik. Ketika tidak ada koreksi institusional yang tegas, pembiaran akan selalu dibaca sebagai persetujuan diam-diam.
Fenomena ini mencerminkan pembusukan etika dalam ruang kekuasaan: tampak rapi di permukaan, tetapi menggerogoti kepercayaan dari dalam. Menuntut publik untuk memahami konteks pribadi seorang kader bukanlah ajakan dialog, melainkan arogansi simbolik yang meremehkan akal sehat kolektif. Dalam demokrasi yang kian dewasa, loyalitas tanpa nalar bukanlah estafet kepemimpinan yang layak diwariskan, melainkan resep pasti bagi krisis legitimasi yang berulang.
Sebagai penutup, Romadhon Jasn menegaskan bahwa “integritas kader diuji bukan saat memuji kejayaan pemimpin, melainkan ketika berani berdiri di sisi kebenaran meskipun harus berseberangan dengan kekuasaan; di situlah politik kembali menjadi jalan pengabdian bermartabat, bukan ruang pembenaran atas kesalahan pimpinan.”
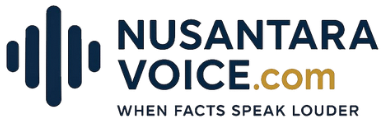







Komentar