Oleh: Romadhon Jasn, Aktivis Nusantara
Rompi oranye kini bukan lagi simbol kejut, melainkan rutinitas. Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjerat kepala daerah satu per satu. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang adalah dua dari sekian nama yang muncul dalam operasi tangkap tangan dengan pola nyaris seragam. Bagi masyarakat sipil, ini bukan lagi sekadar kriminalitas elite, melainkan tanda bahwa demokrasi lokal sedang bocor dan dibiarkan tanpa koreksi serius.
Masalahnya bukan terutama soal moral individu. Akar persoalannya terletak pada desain sistem. Pilkada langsung telah menjelma ajang politik berbiaya ekstrem. Berbagai kajian memperkirakan calon bupati atau wali kota harus menyiapkan dana Rp20–50 miliar, sementara calon gubernur bisa menghabiskan lebih dari Rp100 miliar. Angka ini jauh melampaui penghasilan sah selama satu periode jabatan. Sejak hari pertama dilantik, kepala daerah sejatinya sudah menanggung utang politik.
Ketika ongkos untuk berkuasa lebih mahal daripada penghasilan resmi, korupsi berhenti menjadi penyimpangan. Ia berubah menjadi mekanisme bertahan hidup. Skema ijon proyek, jual beli jabatan, dan manipulasi perizinan muncul bukan semata karena lemahnya pengawasan, melainkan karena sistem politik memaksa pejabat publik membayar kembali ongkos kekuasaan. Dalam konteks ini, korupsi menjadi “murah” justru karena demokrasi kita terlampau mahal.
Ironinya, negara ikut membiayai mahalnya prosedur itu. Pemilu dan Pilkada 2024 menyedot anggaran lebih dari Rp70 triliun. Namun investasi raksasa tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas pemerintahan daerah. Yang lahir justru parade kepala daerah keluar-masuk ruang pemeriksaan KPK. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi demokrasi substantif tertatih.
Tak mengherankan bila masyarakat sipil mulai menggugat pilkada langsung mekanisme yang dulu dielu-elukan sebagai puncak Reformasi 1998. Kini pilkada kerap dipersepsikan sebagai demokrasi pasar gelap: suara rakyat dibeli murah, sementara kebijakan publik digadaikan mahal. Undang-Undang Pilkada yang berlaku gagal menjawab realitas biaya politik yang kian brutal.
Di tengah kejenuhan publik, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD kembali mengemuka. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyebut opsi tersebut. Gagasan ini mendapat dukungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan alasan efisiensi biaya politik dan penekanan praktik politik uang.
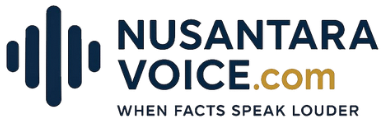







Komentar