Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati tonggak sejarah penting yang lahir dari semangat persatuan Sumpah Pemuda 1928. Hampir seabad berlalu, nilai-nilai itu tetap relevan. Sebab, di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi, persatuan dan kebijaksanaan dalam bermedia justru menjadi tantangan baru bagi generasi muda Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa Sumpah Pemuda adalah bentuk kesadaran kolektif bangsa. Menurut teori nasionalisme Ernest Renan, bangsa terbentuk bukan semata karena faktor ras atau wilayah, tetapi karena “kehendak untuk hidup bersama” (a daily plebiscite). Semangat inilah yang dulu menggerakkan para pemuda dari berbagai daerah untuk mengikrarkan satu tekad: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia.
Kini, di era digital, semangat itu diuji oleh perpecahan wacana, polarisasi politik, dan konflik diksi di ruang publik. Media sosial yang seharusnya menjadi alat koneksi, sering kali justru menjadi sumber disinformasi dan ujaran kebencian.
Dalam konteks inilah, pesan Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menjadi sangat relevan. Saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, ia menegaskan bahwa “Pemuda bukan pelengkap sejarah, tetapi penentu sejarah.”
Pesan ini mengandung makna mendalam: bahwa pemuda bukan sekadar penonton perubahan, tetapi aktor utama dalam menulis sejarah bangsa. Teori Human Capital dari Theodore Schultz menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia khususnya generasi muda merupakan kunci kemajuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Maka, ketika ASR menekankan pentingnya kreativitas dan keilmuan sebagai bentuk perjuangan masa kini, itu bukan sekadar seruan moral, tetapi strategi pembangunan berkelanjutan.
Gubernur ASR juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan etika sosial. Dalam konteks komunikasi publik, diksi yang santun menjadi bentuk kecerdasan sosial. Seperti dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “Kebesaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya berbicara, tetapi dari kemampuannya untuk berbicara dengan hormat.”
Kebebasan berekspresi yang diberikan oleh media sosial memang membawa manfaat besar, namun tanpa kedewasaan dalam menggunakannya, ia bisa berubah menjadi alat perpecahan. Teori Social Responsibility dalam komunikasi massa menegaskan bahwa kebebasan media harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika publik.
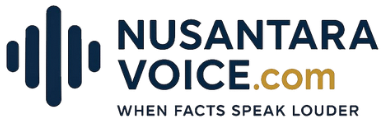







Komentar