Persoalan utama terletak pada kualitas penciptaan lapangan kerja. Mayoritas pekerjaan baru masih berasal dari sektor informal dan jasa berproduktivitas rendah, dengan tingkat perlindungan sosial yang terbatas. Banyak rumah tangga hidup dengan pendapatan yang tidak pasti, sementara peluang untuk naik kelas secara ekonomi tetap sempit. Kondisi ini menjelaskan mengapa perbaikan indikator pengangguran tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan riil. Inflasi yang relatif terkendali memang membantu menjaga daya beli secara agregat, tetapi tekanan harga pangan dan transportasi tetap dirasakan lebih berat oleh kelompok berpendapatan rendah. Di sinilah statistik makro sering gagal menangkap realitas mikro. Kisah anak di NTT tersebut menjadi simbol bahwa bagi sebagian warga, pertumbuhan ekonomi masih terasa abstrak.
Dimensi lain yang patut dicermati adalah peran sektor keuangan. Pertumbuhan kredit sepanjang 2025 berada di kisaran 9,7 persen, relatif moderat di tengah likuiditas perbankan yang longgar. Dana menganggur diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2.400 triliun, sementara kepemilikan Surat Berharga Negara oleh perbankan menembus Rp 1.200 triliun. Preferensi terhadap aset berisiko rendah mencerminkan kehati-hatian lembaga keuangan. Namun pada level makro, situasi ini menunjukkan lemahnya transmisi kebijakan moneter ke sektor produktif. Likuiditas besar tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi investasi riil. UMKM kesulitan mengakses pembiayaan murah, ekspansi usaha berjalan tertahan, dan penciptaan kerja berkualitas ikut melambat. Jika pola ini berlanjut, proyeksi pertumbuhan 2026 di kisaran 4,9–5,7 persen akan semakin sulit diwujudkan.
Di sisi fiskal, tantangan kian nyata. Penerimaan negara 2025 tidak sepenuhnya mencapai target, terutama dari sektor perpajakan. Moderasi aktivitas usaha dan pelemahan harga komoditas turut memengaruhi basis penerimaan. Akibatnya, defisit APBN melebar dan mendekati batas maksimum 3 persen terhadap PDB. Pada saat yang sama, kebutuhan belanja justru meningkat—mulai dari pembayaran bunga utang, penguatan perlindungan sosial, hingga investasi sumber daya manusia. Ketika ruang fiskal menyempit, negara kehilangan daya untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif. Tanpa konsolidasi fiskal yang kredibel, Indonesia berisiko memasuki 2026 dengan kombinasi yang tidak sehat: defisit tinggi, kebutuhan pembiayaan besar, dan ketergantungan yang meningkat pada utang. Dalam kondisi seperti itu, APBN berpotensi kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen stabilisasi sekaligus alat pemerataan.
Situasi ini menuntut reorientasi kebijakan pembangunan. Kebijakan fiskal perlu lebih diarahkan pada penciptaan kerja produktif melalui penguatan UMKM, reformasi pasar tenaga kerja, dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Diversifikasi ekonomi harus dipercepat dengan membangun sektor bernilai tambah tinggi—manufaktur hijau, teknologi, dan ekonomi digital—agar Indonesia keluar dari jebakan komoditas. Sektor keuangan perlu didorong lebih aktif mendukung sektor riil melalui penguatan insentif kredit produktif dan pengurangan ketergantungan pada instrumen bebas risiko. Pada saat yang sama, pemerintah harus menyiapkan strategi keberlanjutan fiskal yang komprehensif menuju 2026: memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, menata ulang belanja agar lebih produktif, serta memastikan setiap rupiah belanja publik benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas.
Pertumbuhan ekonomi 2025 mencerminkan ketahanan makro yang patut dihargai. Namun ia juga menegaskan keterbatasan model pembangunan yang masih bertumpu pada konsumsi dan komoditas. Dengan rasio Gini yang tetap tinggi, kemiskinan yang masih signifikan, kualitas pekerjaan yang belum membaik secara struktural, serta ruang fiskal yang semakin menyempit, Indonesia berada pada persimpangan strategis. Pilihan ke depan bukan sekadar antara tumbuh atau tidak tumbuh, melainkan antara mempertahankan pola lama atau melakukan transformasi.
Pertumbuhan ekonomi seharusnya menjadi sarana pembebasan dari kemiskinan, jembatan mobilitas sosial, dan fondasi keadilan antargenerasi. Tanpa keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural—di bidang fiskal, industri, keuangan, dan pembangunan manusia—angka-angka makro akan terus tampak menjanjikan, sementara ketimpangan dan kerentanan sosial tetap mengendap di bawah permukaan.
Dan ketika seorang anak masih kehilangan harapan hanya karena tidak memiliki buku tulis dan pensil, kita perlu bertanya dengan jujur: untuk siapa sesungguhnya pertumbuhan itu berlangsung?
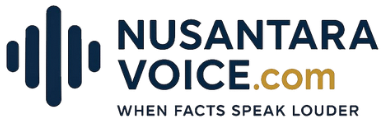













Komentar