Oleh: Akril Abdillah
Partai Golkar Sulawesi Tenggara tengah menghadapi ujian serius yang tidak bisa lagi dianggap sebagai dinamika internal biasa. Persoalan ini menyentuh jantung demokrasi internal partai dan memunculkan pertanyaan mendasar yang wajar diajukan publik. Apakah Golkar masih berdiri sebagai partai kader, atau perlahan berubah menjadi partai keluarga?
Pertanyaan itu mengemuka seiring konfigurasi kepemimpinan yang kini berlaku di tubuh Golkar Sultra. Darwin menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara, sementara istrinya, Rhika Purwaningsih, memimpin DPD II Golkar Kabupaten Muna Barat. Fakta ini bukan sekadar kebetulan struktural, melainkan sebuah anomali yang belum pernah tercatat secara terang dalam sejarah panjang Golkar. Karena itu, isu ini tidak bisa direduksi menjadi persoalan teknis atau administratif semata. Ini adalah persoalan etik kekuasaan.
Memang benar, tidak ada larangan eksplisit dalam AD/ART Partai Golkar yang menyatakan bahwa suami dan istri tidak boleh memimpin struktur partai pada jenjang yang berbeda. Namun politik tidak hanya hidup dari pasal-pasal tertulis. Politik justru hidup dari kepantasan, rasa keadilan, dan persepsi publik. Ketika kekuasaan struktural di tingkat provinsi dan kabupaten berpusat pada satu rumah tangga, wajar jika muncul kecurigaan dan kegelisahan, baik di kalangan kader maupun masyarakat luas. Apakah Golkar Sultra benar-benar kehabisan kader? Ataukah kekuasaan sedang dikonsentrasikan dan diorkestrasikan secara sadar dalam lingkaran terbatas?
Dalam struktur Golkar, Ketua DPD I memiliki pengaruh strategis terhadap kehidupan organisasi di tingkat kabupaten dan kota. Pengaruh itu mencakup arah konsolidasi, legitimasi kepengurusan, dinamika Musda, hingga penilaian loyalitas dan disiplin kader. Dalam situasi normal, kewenangan tersebut sudah sangat besar. Namun ketika salah satu DPD II dipimpin oleh pasangan hidup Ketua DPD I, maka batas antara kewenangan struktural dan kepentingan personal menjadi kabur. Di titik inilah konflik kepentingan tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan nyata secara etis. Dalam politik modern, konflik kepentingan tidak harus menunggu penyalahgunaan kekuasaan untuk dianggap bermasalah. Cukup dengan adanya potensi dan persepsi publik, legitimasi institusi sudah mulai tergerus.
Situasi ini juga mengirim pesan yang sangat problematik bagi kader Golkar di daerah. Ketika jabatan strategis tampak lebih mudah diraih melalui relasi keluarga ketimbang proses panjang kaderisasi, maka semangat kompetisi sehat dan kepercayaan terhadap mekanisme internal partai akan melemah. Regenerasi yang selama ini diagungkan berisiko menjadi sekadar jargon, bukan praktik nyata. Golkar yang seharusnya membina dan menguatkan kader justru bisa berubah menjadi organisasi yang mematahkan harapan kadernya sendiri.
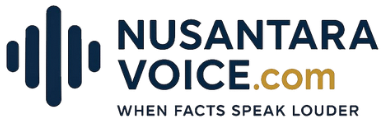










Komentar