Oleh : Rakhmat Djabar
Peraih Nobel Ekonomi Douglass North mengingatkan bahwa krisis ekonomi hampir selalu berakar pada kegagalan institusi, bukan semata pada fluktuasi pasar. Ketika negara gagal menjaga kredibilitas aturan main, pasar akan menghukum dengan cepat—dan tanpa kompromi. Apa yang terjadi di pasar modal Indonesia pada awal 2026 adalah contoh klasik dari tesis tersebut.
Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 7,35 persen pada 28 Januari, disusul volatilitas ekstrem sepanjang pekan berikutnya (bergerak liar di rentang 7.922–8.329), bukanlah sekadar koreksi siklikal. Ini adalah sinyal politik dari pasar: sebuah vote of no confidence terhadap kualitas tata kelola ekonomi Indonesia.
Secara teoritik, episode ini mendekati apa yang dikenal sebagai Minsky moment—fase ketika stabilitas semu runtuh karena risiko laten akhirnya terkuak. Namun di Indonesia, pemicunya bukan sekadar leverage finansial, melainkan kombinasi mematikan antara konsentrasi kepemilikan, lemahnya transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), dan pengawasan yang terlalu kompromistis.
Free float saham Indonesia masih berada di kisaran 7–8 persen—jauh tertinggal dibanding pasar berkembang Asia yang rata-rata sudah melampaui 20 persen. Struktur ini menciptakan pasar yang dangkal, mudah digerakkan, dan sangat rentan terhadap manipulasi. Dalam konteks seperti ini, volatilitas bukan anomali; ia adalah keniscayaan.
Peringatan sudah lama disampaikan, termasuk melalui asesmen MSCI sejak 2025. Maka ketika muncul sinyal interim freeze, pasar bereaksi secara rasional: net sell asing sekitar Rp13,9 triliun dalam sepekan, dengan lonjakan nilai transaksi hingga Rp68 triliun. Ini bukan sekadar kepanikan. Ini adalah penyesuaian risiko terhadap negara yang dianggap gagal menjaga kredibilitas institusional.
Investor keluar bukan karena sentimen, melainkan karena premi risiko politik meningkat: aturan mudah berubah, pengawasan tumpul ke atas, dan penegakan hukum terasa selektif.
Mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia memang patut diapresiasi sebagai tanggung jawab moral. Namun secara politik-ekonomi, itu adalah pengakuan diam-diam atas kegagalan sistemik. Ini bukan soal individu; ini tentang desain kelembagaan yang memungkinkan regulatory capture tumbuh subur—ketika regulator terlalu dekat dengan industri, kehilangan jarak kritis, dan akhirnya lebih sibuk menjaga stabilitas semu ketimbang menegakkan disiplin pasar.
Respons pemerintah berupa delapan agenda reformasi—kenaikan free float hingga 15 persen, penguatan UBO, demutualisasi bursa, hingga instrumen stabilisasi—secara teknokratis tampak menjanjikan. Tetapi problem utamanya adalah watak reaktifnya. Reformasi baru digerakkan ketika reputasi internasional terancam menjelang evaluasi MSCI Mei 2026.
Di sinilah politik kebijakan diuji. Apakah negara sungguh ingin membangun pasar modal yang sehat, atau sekadar mempertahankan status demi citra?
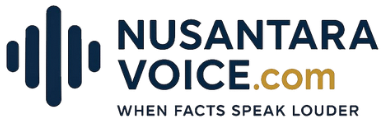







Komentar