JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM— Di balik gemerlap retorika reformasi pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kini terperangkap dalam pusaran dugaan pelanggaran etik yang menjerat sekretarisnya sendiri, David Yama. Kasus ini, yang meledak pada pertengahan Agustus 2025, bukan sekadar noda administratif, melainkan gejala mendalam dari degradasi moral yang menggerogoti fondasi institusi negara. Dua aduan utama menjadi sorotan: pertama, manipulasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaporkan oleh pegawai internal, menunjukkan bagaimana prosedur meritokrasi dikorupsi untuk kepentingan pribadi; kedua, penyalahgunaan wewenang dengan mengajak istri dalam perjalanan dinas, sebagaimana diadukan kelompok mahasiswa ke DKPP dan Kementerian Dalam Negeri. Ini bukan insiden biasa, tapi manifestasi dari arogansi kekuasaan yang mengaburkan batas antara publik dan privat, mengkhianati esensi demokrasi sebagai arena keadilan kolektif.
Latar belakang Yama sebagai birokrat kawakan di Kementerian Dalam Negeri sejak 2002, dengan posisi kunci di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kesatuan Bangsa, seharusnya menjadi jaminan integritas. Namun, dugaan ini justru mengungkap paradoks birokrasi Indonesia: mereka yang ditugaskan menegakkan etika sering kali menjadi korban godaan kekuasaan. Pegiat pemilu dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Brahma Aryana, menegaskan bahwa DKPP memegang peran strategis dalam undang-undang untuk menjaga kode etik, tapi penegakan hukumnya harus berkualitas, bukan sekadar kuantitas aduan. Ribuan kasus dari Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi bukti, jika internal lembaga ompong, maka seluruh sistem elektoral terancam runtuh.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengklaim proses penanganan berjalan secara internal, berbeda dari kasus eksternal melibatkan KPU atau Bawaslu. Namun, jawabannya yang minim rincian “sudah diproses” memicu keraguan akan komitmen transparansi. Dalam konteks ribuan aduan etik sepanjang 2024-2025, pola “penanganan internal” ini sering kali menjadi tameng untuk menutupi kelemahan struktural. Aktivis melihatnya sebagai bentuk proteksi diri, di mana etika hanya diterapkan pada yang lemah, sementara pejabat tinggi lolos dari pengawasan publik.
Dari sudut etika filosofis, pelanggaran seperti ini mencerminkan korupsi intelektual yang merusak republik. Ketika seorang pejabat membengkokkan aturan untuk keuntungan pribadi, ia tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mengikis kepercayaan rakyat pada institusi yang seharusnya netral. Manipulasi PPPK adalah contoh nepotisme yang menghancurkan meritokrasi, sementara penyalahgunaan dinas menunjukkan mentalitas feodal di era demokrasi. Ini adalah gejala sistemik, di mana kekuasaan bukan alat pelayanan, tapi instrumen dominasi.
Jaringan Aktivis Nusantara (JaN) menilai kasus Yama sebagai titik balik untuk reformasi mendalam di DKPP. “Tidak ada tebang pilih dalam penegakan etik, baik internal maupun eksternal,” tegas Rido Sekjend JAN kepada awak media, Minggu (24/8/2025).
Desakan ini didasari kegagalan Pemilu 2024 yang penuh tudingan kecurangan, dari intervensi hingga manipulasi suara. JAN mengapresiasi masyarakat yang aktif melaporkan dugaan pelanggaran, menegaskan bahwa pengawasan publik adalah kunci agar DKPP tetap kredibel.
Implikasi lebih luas dari kasus ini menyentuh ekosistem demokrasi nasional. DKPP, sebagai penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), seharusnya menjadi benteng independen. Namun, dengan peningkatan aduan etik hingga 30% pasca-2024, termasuk suap dan konflik kepentingan, keraguan atas netralitasnya semakin membesar. JAN menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemantauan terus-menerus terhadap keputusan DKPP, agar penyimpangan tidak menjadi norma.
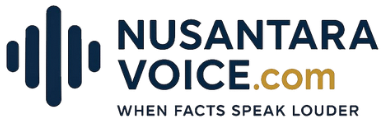







Komentar